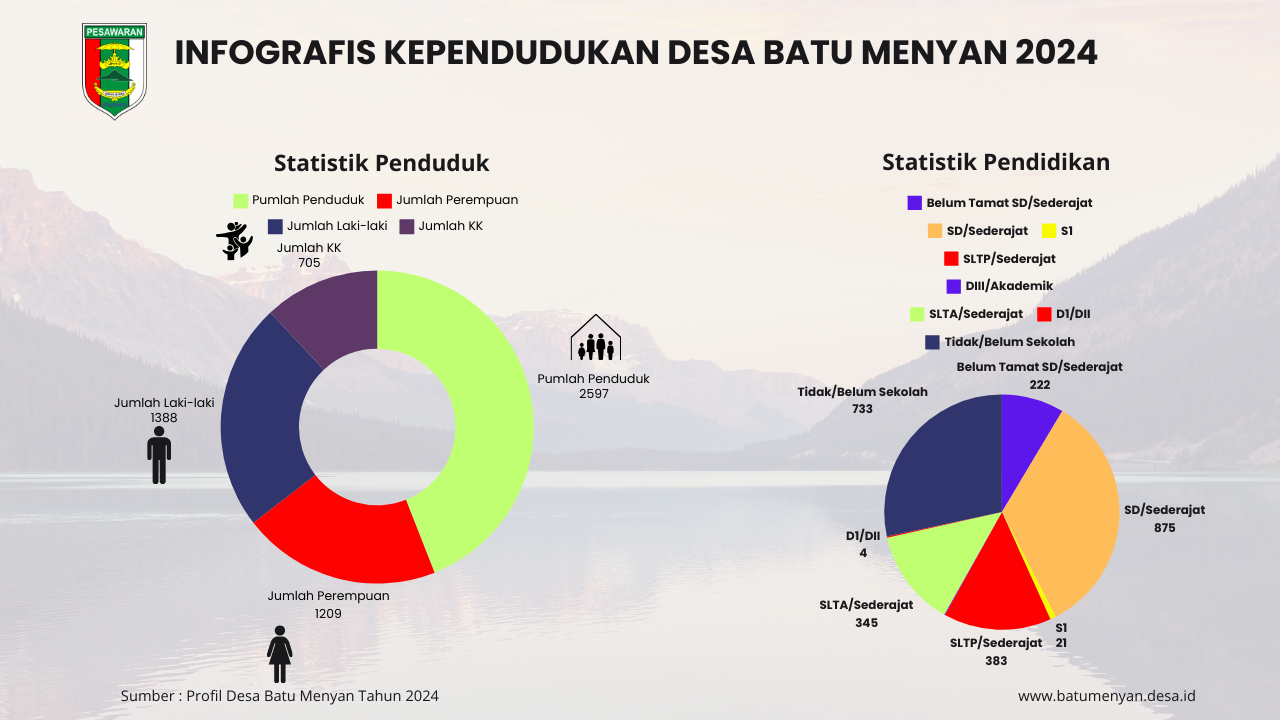Pembangunan desa hari ini kerap dipromosikan sebagai bukti keberhasilan negara menghadirkan keadilan dari pinggiran. Dana desa mengalir, infrastruktur tumbuh, dan program pemberdayaan terus digulirkan. Desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan nasional. Namun, di balik geliat pembangunan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang belum juga diselesaikan secara serius oleh negara, yakni ketidakpastian nasib aparatur desa.
Padahal secara normatif, keberadaan aparatur desa telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 angka 3 UU Desa menegaskan bahwa perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lebih lanjut, Pasal 48 menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Artinya, secara hukum, aparatur desa adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan.
Namun, pengakuan normatif tersebut belum diiringi dengan kepastian status dan jaminan masa depan. Dalam Pasal 66 ayat (1) UU Desa, disebutkan bahwa perangkat desa berhak memperoleh penghasilan tetap, tunjangan, serta jaminan kesehatan. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur sumber penghasilan tetap perangkat desa berasal dari APBDesa. Meski demikian, regulasi ini belum menyentuh aspek paling krusial: jaminan hari tua, pensiun, dan kepastian status kepegawaian.
Aparatur desa hingga kini tidak masuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di sisi lain, mereka juga tidak sepenuhnya dilindungi oleh rezim ketenagakerjaan sebagaimana pekerja formal pada umumnya. Akibatnya, aparatur desa terjebak dalam status hukum yang abu-abu: dituntut profesional, dibebani tanggung jawab besar, namun minim perlindungan.
Beban kerja aparatur desa justru semakin berat pasca lahirnya berbagai regulasi turunan UU Desa. Mulai dari kewajiban perencanaan melalui RPJMDes dan RKPDes, pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hingga tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Kesalahan administratif kerap berujung persoalan hukum, sementara pendampingan dan perlindungan hukum bagi aparatur desa sangat terbatas.
Lebih ironis lagi, dalam Pasal 51 UU Desa, perangkat desa dapat diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun. Namun, ketentuan ini tidak diiringi dengan skema jaminan purna tugas yang layak. Pengabdian puluhan tahun berakhir tanpa pensiun, tanpa jaminan penghasilan, dan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Sebuah ironi dalam negara hukum yang menjunjung asas keadilan sosial.
Jika negara sungguh-sungguh ingin membangun desa secara berkelanjutan, maka pembangunan tidak boleh semata dimaknai sebagai pembangunan fisik dan serapan anggaran. Pembangunan manusia, khususnya aparatur desa, harus menjadi prioritas utama. Tanpa kepastian status dan perlindungan hukum bagi aparatur desa, pembangunan desa sesungguhnya berdiri di atas fondasi yang rapuh.
Negara tidak boleh terus menunda. Penataan status aparatur desa, penguatan jaminan sosial, kepastian masa depan, dan perlindungan hukum harus segera diwujudkan melalui kebijakan yang tegas dan berpihak. Hal ini bukan sekadar tuntutan moral, melainkan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.
Desa boleh terus membangun. Namun negara tidak boleh membiarkan aparaturnya terus menunggu dalam ketidakpastian.